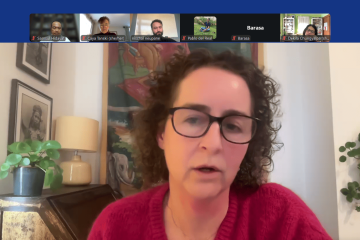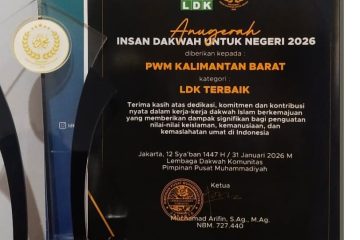Oleh Dr. Samsul Hidayat, M.A.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat
Pada Jumat, 30 Mei 2025, Aula At-Tanwir PWM Kalbar menjadi ruang kontemplasi dan dialektika pemikiran bagi kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pontianak. Dalam kerangka kegiatan Darul Arqam Madya Nasional (DAMNAS) 2025, diskursus filsafat postmodernisme diangkat sebagai materi utama. Tema besarnya, “Rekonstruksi Gerakan IMM di Era Matinya Kepakaran”, bukan sekadar provokatif, melainkan representasi kegelisahan intelektual IMM dalam menghadapi realitas zaman yang ditandai oleh krisis otoritas, relativisme kebenaran, dan euforia digital.
1. Matinya Kepakaran: Sebuah Tafsir Kontekstual
Tema kegiatan ini meminjam istilah “death of expertise” yang dicetuskan oleh Tom Nichols, seorang ilmuwan politik asal Amerika. Istilah ini menggambarkan fenomena pudarnya otoritas pakar dalam masyarakat yang semakin mengagungkan opini pribadi dan informasi instan yang dangkal. Dalam konteks Indonesia, terlebih di ranah gerakan mahasiswa Islam seperti IMM, kondisi ini menjadi tantangan epistemologis sekaligus praksis. Kepakaran tidak lagi dirujuk sebagai sumber kebenaran, melainkan disubordinasikan oleh algoritma media sosial dan narasi populis yang viral namun miskin validitas.
IMM, sebagai gerakan kader, intelektual, dan dakwah, tidak bisa bersikap netral atas realitas ini. IMM harus merekonstruksi dirinya sebagai pusat pembentukan kepakaran, bukan sekadar pelabelan “aktivis” atau “kader militan”. Kepakaran dalam tradisi Islam dan Muhammadiyah adalah hasil dari kesungguhan intelektual, kontemplasi spiritual, dan kepekaan sosial—yang tidak dapat ditumbuhkan hanya dari selebaran digital atau kutipan TikTok berdurasi 60 detik.
2. Filsafat Postmodernisme dan Kritik terhadap Modernitas
Postmodernisme, sebagaimana dijelaskan dalam materi DAMNAS, adalah aliran pemikiran yang muncul sebagai kritik atas proyek modernitas. Jika modernisme percaya pada kemajuan, rasionalitas, dan narasi besar (grand narrative), maka postmodernisme meragukan semuanya. Postmodernisme mencurigai kebenaran yang diklaim universal, mempertanyakan narasi dominan, dan menegaskan pluralitas perspektif serta fragmentasi identitas.
IMM harus sadar bahwa postmodernisme bukan sekadar wacana akademik Barat. Ia telah merasuk ke dalam budaya populer, konten digital, bahkan cara kita menilai keadilan, agama, dan ilmu pengetahuan. Ketika nilai-nilai menjadi relatif dan semua perspektif dianggap setara tanpa hirarki, maka tugas kader IMM bukan hanya memahami, tetapi mengkritisi dan menyaringnya secara bijak.
3. Relativisme Nilai dan Kebenaran: Antara Dekonstruksi dan Dekadensi
Salah satu buah dari postmodernisme adalah relativisme nilai. Dalam relativisme, tidak ada kebenaran absolut; semua hanya konstruksi sosial atau subjektivitas individu. Bagi IMM, ini bisa menjelma menjadi sikap permisif terhadap segala hal, termasuk dalam masalah etika, agama, dan perjuangan ideologis.
Namun kita harus bijak. Relativisme dalam postmodernisme tidak selalu destruktif. Ia bisa menjadi peringatan agar kita tidak terjebak dalam klaim monopoli kebenaran. Islam pun, melalui prinsip la ikraha fid din, mengajarkan pentingnya kebebasan berkeyakinan. Tetapi, relativisme menjadi problematis ketika membunuh komitmen terhadap nilai, menjadikan IMM apatis terhadap kebenaran, dan terombang-ambing oleh opini mayoritas semu.
IMM harus mengembangkan kemampuan membedakan antara pluralitas epistemik dan nihilisme moral. Kritik terhadap universalisme modern harus disandingkan dengan komitmen terhadap nilai-nilai keadaban, kejujuran, keilmuan, dan keadilan.
4. IMM di Era Post-Kebenaran: Menjadi Oase Ilmiah dan Spiritual
Kader IMM hari ini hidup dalam zaman post-truth, di mana emosi dan opini lebih dominan daripada fakta dan nalar. Dalam masyarakat yang semakin anti-intelektual, IMM tidak boleh sekadar menjadi pengikut tren atau pemadam kebakaran dalam polemik-polemik viral.
IMM harus mengambil peran sebagai oase keilmuan dan spiritualitas. Ini bisa diwujudkan dengan beberapa langkah strategis:
-
Membangun budaya membaca dan menulis di kalangan kader sebagai dasar kepakaran.
-
Menumbuhkan tradisi debat ilmiah, bukan debat kusir. IMM harus menciptakan ruang-ruang pertemuan pemikiran lintas disiplin.
-
Menginternalisasi nilai-nilai tarjih Muhammadiyah, yang menjunjung tinggi argumentasi rasional, ijtihad kolektif, dan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat.
-
Menggunakan media sosial secara bijak sebagai sarana dakwah intelektual, bukan kontestasi eksistensi.
5. Menghidupkan Kepakaran: Jalan IMM Menuju Masyarakat Ilmu
Rekonstruksi gerakan IMM harus dimulai dari membangun kembali orientasi gerakan. IMM tidak hanya butuh aktivis lapangan, tetapi juga butuh kader-kader epistemik—mereka yang menguasai teori, metodologi, dan tradisi keilmuan Islam maupun kontemporer. Kepakaran adalah hasil dari mujahadah intelektual yang konsisten dan rendah hati.
Dalam pandangan Islam, kepakaran bukan sekadar akumulasi pengetahuan, melainkan kesadaran akan tanggung jawab moral atas ilmu yang dimiliki. Dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang berilmu akan ditinggikan derajatnya. IMM, dengan semua warisan keilmuannya, mesti kembali menjadikan ayat ini sebagai inspirasi perjuangan kader.
Muhammadiyah sendiri, sejak KH Ahmad Dahlan hingga Prof. Haedar Nashir, telah menekankan pentingnya integrasi antara ilmu dan amal, antara akademik dan praksis sosial. IMM sebagai bagian integral dari gerakan ini, harus menyadari bahwa eksistensinya hanya bermakna bila mampu menjadi jembatan antara tradisi intelektual dan tantangan zaman.

Penutup: IMM dan Harapan Masyarakat yang Berkemajuan
Kegiatan Darul Arqam Madya Nasional IMM Kota Pontianak ini tidak hanya menjadi ajang pelatihan, tetapi juga menjadi momentum refleksi ideologis dan rekonstruksi strategi gerakan. IMM bukan gerakan pinggiran. Ia adalah harapan. Harapan akan lahirnya generasi Muslim yang tercerahkan, terdidik, dan terlibat dalam peradaban.
IMM harus tetap menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan keilmuan dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kita tidak bisa mundur oleh zaman, tapi kita juga tidak boleh hanyut dalam arusnya. IMM adalah penentu arah, bukan pengekor zaman.
Di era yang disebut sebagai “matinya kepakaran”, IMM justru harus hidup sebagai ruang kelahiran pakar-pakar baru. Kader IMM harus menjadi pionir dalam membangun masyarakat ilmu, bukan hanya melalui gelar, tetapi melalui etos belajar, integritas moral, dan komitmen terhadap nilai Islam yang mencerahkan.