Madison, US (26/01/2026) – Dalam sebuah forum internasional yang mempertemukan pemimpin agama dan aktivis dari berbagai negara, yang diselenggarakan dalam kerangka The Preparing Religious Environmental Plans (PREP) Program—sebuah inisiatif internasional yang diampu oleh Loka Initiative, University of Wisconsin–Madison—Ambrose Carroll, pendiri gerakan Green the Church, menyampaikan refleksi mendalam mengenai peran gereja kulit hitam (Black Church) dalam memperjuangkan keadilan lingkungan, keberlanjutan, serta penguatan gerakan lintas iman global. Forum ini menjadi ruang dialog strategis bagi para pemimpin agama untuk merumuskan respons berbasis iman terhadap krisis ekologis dan ketimpangan struktural yang dihadapi komunitas rentan di berbagai belahan dunia.
Carroll menegaskan bahwa teologi tidak dapat dipisahkan dari praktik hidup sehari-hari. Menurutnya, pemahaman keagamaan harus mendorong tindakan nyata, mulai dari praktik berkelanjutan seperti daur ulang dan energi terbarukan, hingga keterlibatan politik untuk memperjuangkan perubahan sosial dan ekonomi. “Kita perlu memastikan bahwa komunitas iman memiliki kekuatan untuk hadir di balai kota, di parlemen negara bagian, dan menyuarakan keadilan yang mereka butuhkan,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, Carroll menanggapi pertanyaan mengenai perbedaan antara gereja-gereja kulit hitam yang relatif mapan secara ekonomi dan gereja-gereja kecil di kawasan yang lebih terpinggirkan. Ia menolak anggapan bahwa Black Church adalah entitas yang homogen. Menurutnya, banyak gereja yang justru berada di “zona tantangan”, di mana kebutuhan dasar jemaat sering kali lebih mendesak dibandingkan wacana lingkungan yang dianggap mahal atau elitis.
“Kami memulai percakapan dari kebutuhan yang paling dirasakan,” jelas Carroll. Ia mencontohkan bagaimana bantuan sederhana, seperti perbaikan fasilitas gereja atau dukungan program komunitas, dapat menjadi pintu masuk untuk diskusi yang lebih luas tentang lingkungan. Dari titik inilah, kesadaran ekologis tumbuh secara organik dan berakar pada realitas hidup jemaat.
Isu gentrifikasi juga menjadi sorotan. Carroll menjelaskan bahwa banyak gereja yang secara geografis berada di kawasan miskin, namun jemaatnya tidak lagi tinggal di lingkungan tersebut. Ketegangan antara gereja dan komunitas sekitar menjadi tantangan tersendiri dalam membangun gerakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan. Kondisi ini menuntut pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan sejarah setempat.
Forum tersebut juga menampilkan diskusi tentang pengalaman kolaborasi lintas iman. Carroll berbagi pengalamannya bekerja sama dengan komunitas Yahudi, Katolik, Muslim, Hindu, dan Buddha dalam berbagai inisiatif lingkungan. Ia mengakui bahwa kerja lintas iman tidak selalu mudah, karena sering kali dibayangi oleh stereotip dan ketegangan historis. Namun, menurutnya, ruang aman untuk dialog dan kerja bersama justru menjadi kunci untuk meruntuhkan prasangka tersebut.
“Kita tidak bisa menghapus perbedaan, tetapi kita bisa belajar untuk hadir bersama,” ujarnya. Carroll menekankan bahwa melihat pemimpin agama dari latar belakang berbeda berjalan berdampingan di ruang publik dapat menjadi simbol harapan yang kuat bagi masyarakat luas.
Dalam konteks kebijakan publik, Carroll mengingatkan bahwa advokasi tidak boleh bersifat top-down atau sekadar mengajak komunitas menandatangani agenda yang tidak mereka pahami. Ia mencontohkan pengalamannya dalam menolak proyek kereta batu bara di Oakland. Alih-alih hanya menyerukan penolakan, Green the Church justru menyelenggarakan bursa kerja hijau dan menghadirkan perusahaan energi bersih untuk menunjukkan alternatif nyata bagi penciptaan lapangan kerja.
Pendekatan holistik ini, menurut Carroll, membuat komunitas tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi subjek yang memahami dan memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dari kesadaran inilah, komunitas iman dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar lahir dari kebutuhan mereka.
Diskusi juga menyinggung dimensi global gerakan lingkungan berbasis iman. Carroll menyebut keterlibatannya dalam jaringan internasional seperti 350.org dan Atlantic Fellows sebagai ruang penting untuk pertukaran pengalaman antara Global North dan Global South. Ia bahkan menceritakan lahirnya Green the Church Kenya sebagai hasil dialog lintas negara yang mempertemukan aktivis dari berbagai konteks budaya dan sosial.
Menutup sesi, Carroll merefleksikan peran pemimpin agama di tengah meningkatnya konflik global dan rezim yang represif. Ia mengajak komunitas iman untuk “belajar berjalan bersama” di tengah perbedaan, seraya menegaskan bahwa kebersamaan lintas iman di ruang publik dapat menghadirkan harapan baru. “Ketika orang melihat kita bersama, mereka melihat kemungkinan dunia yang lebih adil dan manusiawi,” pungkasnya.
Samsul Hidayat Menangkap Pesan Kunci PREP
Diskusi yang disampaikan Ambrose Carroll juga memantik refleksi dari para peserta lintas negara, termasuk dari Indonesia. Samsul Hidayat, dosen IAIN Pontianak sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, menilai bahwa gagasan Carroll memiliki relevansi kuat bagi konteks masyarakat di Global South yang menghadapi tekanan ekologis dan sosial secara bersamaan.
Menurut Samsul, kekuatan utama pemikiran Carroll terletak pada keberhasilannya mengaitkan teologi dengan praktik keseharian dan daya advokasi politik. Penekanan bahwa komunitas iman membutuhkan fondasi spiritual sekaligus kekuatan kolektif dianggap sejalan dengan realitas komunitas keagamaan di Indonesia, yang kerap berada di garis depan krisis lingkungan—mulai dari kebakaran hutan dan lahan, banjir musiman, hingga krisis kesehatan akibat degradasi lingkungan.
Namun demikian, refleksi tersebut juga memunculkan pertanyaan penting: bagaimana membangun kekuatan kolektif untuk keadilan lingkungan di tengah komunitas yang masih disibukkan oleh kebutuhan dasar? Dalam banyak konteks lokal, isu lingkungan sering kali berhadapan langsung dengan persoalan kemiskinan, keterbatasan akses layanan publik, dan ketimpangan struktural.
Dari sudut pandang ini, tantangan utama bagi pemimpin agama bukan hanya menyuarakan kepedulian ekologis, tetapi juga menemukan langkah awal yang realistis—langkah yang mampu menghubungkan perjuangan lingkungan dengan kebutuhan paling nyata yang dirasakan umat. Pendekatan bertahap, yang dimulai dari persoalan sehari-hari seperti kesehatan, penghidupan, dan ruang hidup yang aman, dinilai lebih memungkinkan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis yang berakar dan berkelanjutan.
Refleksi ini memperkuat pesan utama forum PREP bahwa keadilan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial. Gerakan berbasis iman akan memiliki daya hidup yang lebih kuat ketika ia tumbuh dari pengalaman konkret komunitas, bukan sebagai agenda abstrak atau elitis. Dalam konteks inilah, dialog antara iman, sains, dan realitas sosial menjadi bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak.
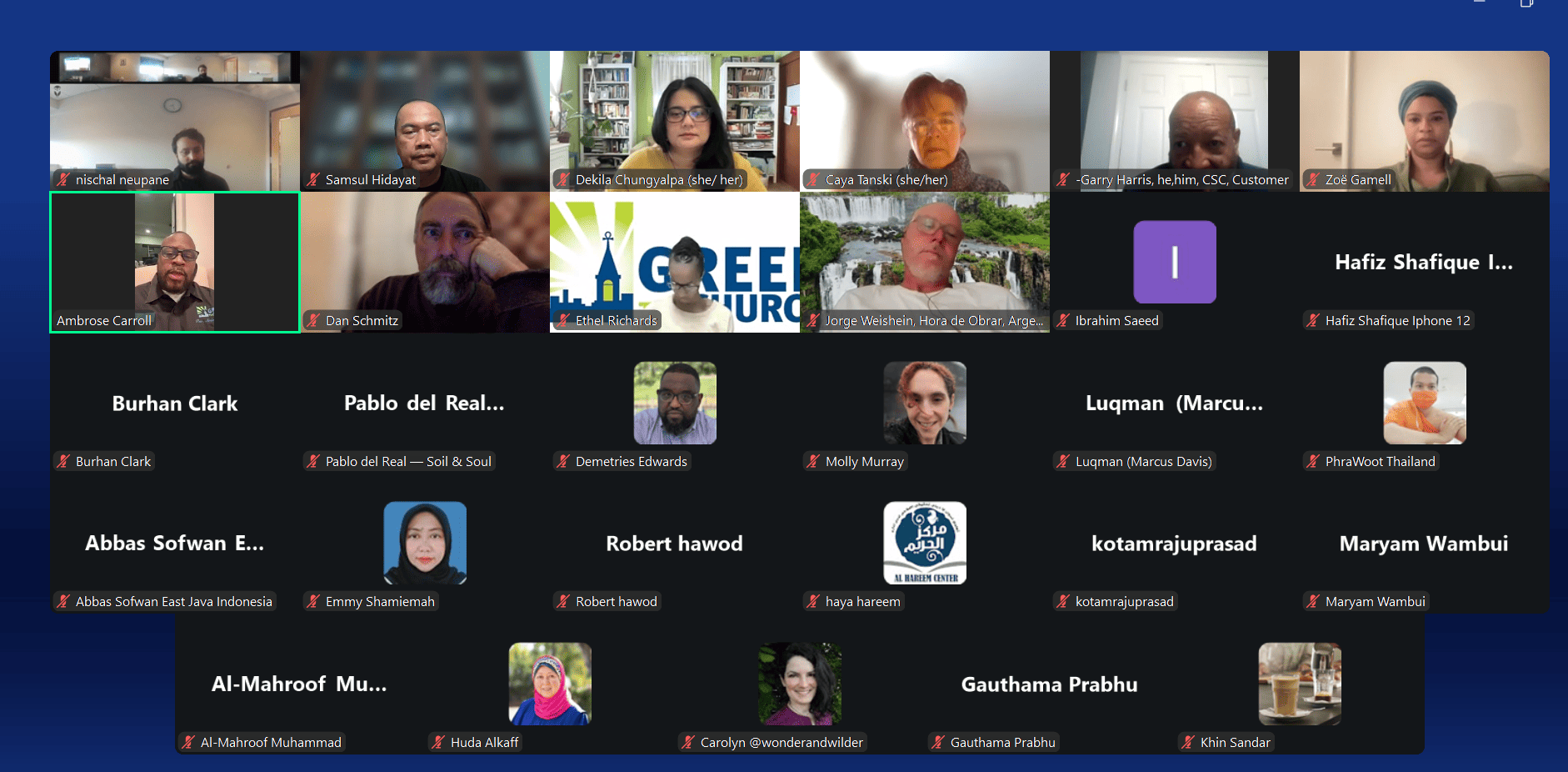
Faith, Environment, and Justice: Ambrose Carroll’s Message at the PREP Forum
Madison (26/01/2026) — At an international forum bringing together religious leaders and activists from across the globe, convened under The Preparing Religious Environmental Plans (PREP) Program—an international initiative hosted by the Loka Initiative at the University of Wisconsin–Madison—Ambrose Carroll, founder of the Green the Church movement, delivered a compelling reflection on the role of the Black Church in advancing environmental justice, sustainability, and the strengthening of global interfaith movements. The forum served as a strategic space for faith leaders to articulate faith-based responses to the ecological crisis and the structural inequalities facing vulnerable communities worldwide.
Carroll emphasized that theology cannot be separated from everyday practice. Religious understanding, he argued, must translate into concrete action—from sustainable practices such as recycling and renewable energy to political engagement aimed at achieving social and economic change. “We need to ensure that faith communities have the power to show up at City Hall, at state capitols, and to advocate for the justice they need,” he said.
During the question-and-answer session, Carroll addressed disparities between economically established Black churches and smaller congregations in more marginalized areas. He rejected the notion of the Black Church as a monolithic entity, noting that many congregations operate in what he described as “challenge zones,” where basic congregational needs often take precedence over environmental agendas perceived as costly or elitist.
“We begin the conversation with the most felt needs,” Carroll explained. He illustrated how modest interventions—such as repairing church facilities or supporting community programs—can open pathways to broader environmental discussions. From this starting point, ecological awareness grows organically, rooted in the lived realities of congregations.
Gentrification also emerged as a key concern. Carroll observed that while many churches remain geographically located in low-income neighborhoods, their congregants may no longer reside there. This disconnect can generate tension between churches and surrounding communities, complicating efforts to build inclusive and just environmental movements. Addressing these challenges, he noted, requires approaches that are sensitive to local social and historical contexts.
The forum further highlighted experiences of interfaith collaboration. Carroll shared insights from working with Jewish, Catholic, Muslim, Hindu, and Buddhist communities on environmental initiatives. He acknowledged that interfaith work is often fraught with stereotypes and historical tensions. Nevertheless, he stressed that creating safe spaces for dialogue and shared action is essential to dismantling prejudice.
“We may not erase differences, but we can learn to be present together,” Carroll said. He underscored the symbolic power of seeing leaders from diverse faith traditions standing side by side in public spaces—a vision that can inspire hope and solidarity within broader society.
On public policy, Carroll cautioned against top-down advocacy that merely asks communities to endorse agendas they do not fully understand. Drawing on his experience opposing coal train projects in Oakland, he explained that Green the Church paired resistance with opportunity by organizing green job fairs and inviting clean-energy companies to present tangible employment alternatives.
This holistic approach, Carroll argued, transforms communities from passive policy subjects into active agents who understand and advocate for their own interests. From such grounded awareness, faith communities can help shape policies that genuinely reflect their needs.
The discussion also explored the global dimension of faith-based environmental movements. Carroll cited his involvement with international networks such as 350.org and Atlantic Fellows as vital platforms for exchanging experiences between the Global North and Global South. He noted that Green the Church Kenya emerged from cross-border dialogue connecting activists across cultural and social contexts.
Closing the session, Carroll reflected on the role of religious leaders amid escalating global conflicts and increasingly repressive regimes. He urged faith communities to “learn how to walk together” across differences, affirming that interfaith presence in public life can cultivate renewed hope. “When people see us together,” he concluded, “they see the possibility of a more just and humane world.”
Samsul Hidayat Captures the Key Messages of PREP
The discussion presented by Ambrose Carroll also prompted reflections from participants across countries, including Indonesia. Samsul Hidayat, a lecturer at IAIN Pontianak and Vice Chair of the Muhammadiyah Regional Leadership of West Kalimantan, observed that Carroll’s ideas resonate strongly with contexts in the Global South, where ecological and social pressures often converge.
According to Samsul, the central strength of Carroll’s perspective lies in his ability to connect theology with everyday practice and political advocacy. The emphasis on faith communities needing both spiritual grounding and collective power aligns closely with the realities of religious communities in Indonesia, many of which stand on the frontlines of environmental crises—ranging from recurring forest and peatland fires and seasonal flooding to public health emergencies caused by environmental degradation.
At the same time, this reflection raises a critical question: how can collective power for environmental justice be built within communities that are still preoccupied with meeting urgent basic needs? In many local contexts, environmental issues directly intersect with poverty, limited access to public services, and structural inequality.
From this standpoint, the primary challenge for religious leaders is not only to articulate ecological concern, but also to identify realistic entry points—steps that meaningfully connect environmental advocacy with the most immediate needs experienced by their congregations. A gradual approach, beginning with everyday concerns such as health, livelihoods, and safe living spaces, is seen as more likely to cultivate ecological awareness that is deeply rooted and sustainable.
This reflection reinforces the core message of the PREP forum: environmental justice cannot be separated from social justice. Faith-based movements gain greater vitality and legitimacy when they emerge from the lived experiences of communities, rather than being framed as abstract or elitist agendas. In this light, dialogue between faith, science, and social reality is not only relevant, but increasingly urgent.


