Madison, United State (09/02/2026) In one of the key sessions of the Preparing Religious Environmental Plans (PREP) program, participants were invited to critically reconsider environmental conservation approaches that are often overly technocratic and disconnected from community realities. The session featured Chantal Elkin, a figure who has spent decades on the frontlines of international conservation and who now champions a more dialogical approach linking faith, values, and environmental stewardship.
Chantal Elkin currently serves as Head of the Beliefs and Values Program at the World Wildlife Fund (WWF). With more than 30 years of experience in international conservation, she is widely recognized for her work on forest and wildlife protection, particularly in addressing the illegal wildlife trade—one of the most serious threats to global biodiversity. What distinguishes Elkin from many other conservation experts, however, is her long-standing focus on the relationship between religion, faith-based values, and conservation practice.
In her presentation, Elkin emphasized that the environmental crisis cannot be resolved solely through scientific or top-down policy approaches. In many parts of the world—especially in the Global South—religious values remain the most trusted moral language within communities. “If we want change that lasts,” she noted, “we have to speak through the values that already live within communities.”
Elkin shared experiences from working with faith communities across Africa, Asia, and Latin America. When faith leaders are engaged from the beginning as equal partners—rather than merely as targets of outreach—conservation initiatives are more likely to be embraced, protected, and passed down across generations. According to Elkin, this approach is far more effective than projects that prioritize technical indicators while overlooking social and spiritual contexts.
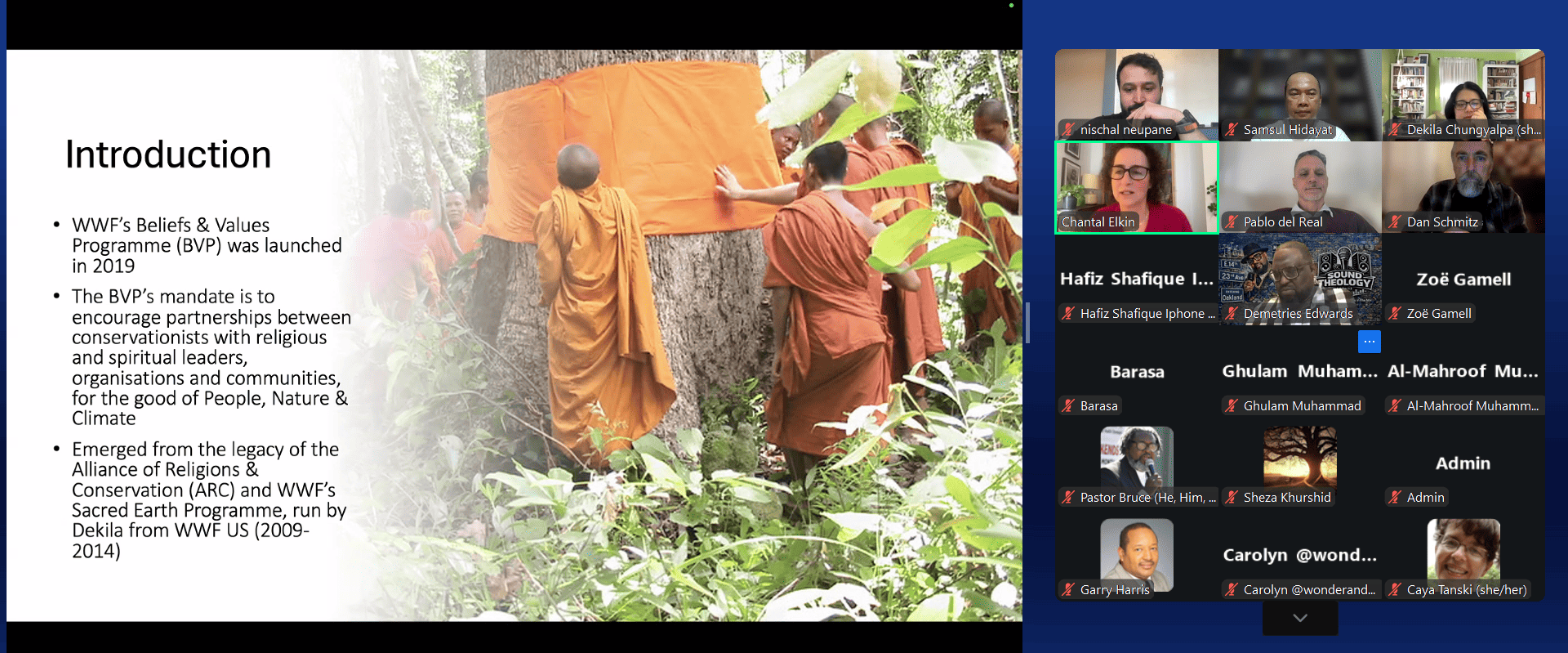
One of Elkin’s central messages was the need to avoid symbolic conservation. She cautioned that many initiatives fail because community participation is treated as a formality, while real decision-making power remains with external actors. Genuine conservation, she argued, must allow communities—including faith communities—to shape the direction, priorities, and methods of projects from start to finish.
Resource limitations also emerged as a major concern during the discussion. Responding to participants from small and under-resourced communities, Elkin stressed that conservation does not always require large budgets. “What matters most are relationships, trust, and consistency,” she said. She pointed to simple yet impactful practices such as shifts in consumption behavior, protection of sacred natural sites, and environmental education through houses of worship as realistic starting points.
For Samsul Hidayat, as a PREP participant from Indonesia, Elkin’s insights resonated deeply. In many regions, including West Kalimantan, deforestation, forest fires, and wildlife degradation are inseparable from people’s beliefs, values, and ways of relating to nature. The approach Elkin offers creates space for more equitable partnerships between global conservation institutions and local faith-based communities.
The session reaffirmed that faith is not an obstacle to conservation, but a powerful and often underutilized asset. Drawing on her long experience at WWF and within global conservation networks, Elkin demonstrated that the future of environmental protection will be shaped by our ability to bridge science, values, and belief systems into a shared movement.
The session also opened space for reflection among participants from different countries. Samsul Hidayat, a PREP participant from Indonesia, raised a question that reflects the concerns of many grassroots faith communities, particularly in the Global South. He highlighted how limited resources often become an initial barrier to faith-based engagement in environmental action.
In his reflection, Samsul asked how small, local faith communities can begin conservation work with very limited resources, and what common mistakes faith-based groups should avoid when forming environmental partnerships. These questions stem from field experiences in which community enthusiasm is often high, but not matched by technical capacity, funding access, or strong networks.
Elkin’s earlier remarks offered a relevant framework for responding to these concerns. She emphasized that faith-based conservation does not need to begin with large-scale projects, but with small, consistent, and spiritually meaningful practices. In this perspective, one of the most common mistakes is attempting to replicate large project models without considering local contexts, or forming partnerships too quickly without ensuring shared values and balanced roles.
For Samsul, this dialogue reinforced the conviction that faith-based environmental work must begin with honesty about limitations, combined with the courage to start from what is already present: social relationships, community trust, and the moral authority of faith leaders. In the Indonesian context—where mosques, Islamic boarding schools, churches, temples, and religious organizations maintain close ties with communities—this approach offers strong potential for rooted, inclusive, and sustainable conservation.
Ultimately, this additional reflection underscores the central message of the PREP session with Chantal Elkin: that the future of conservation is not defined primarily by the size of budgets or the sophistication of tools, but by our capacity to build partnerships that are humble, contextual, and faithful to the living values of communities.
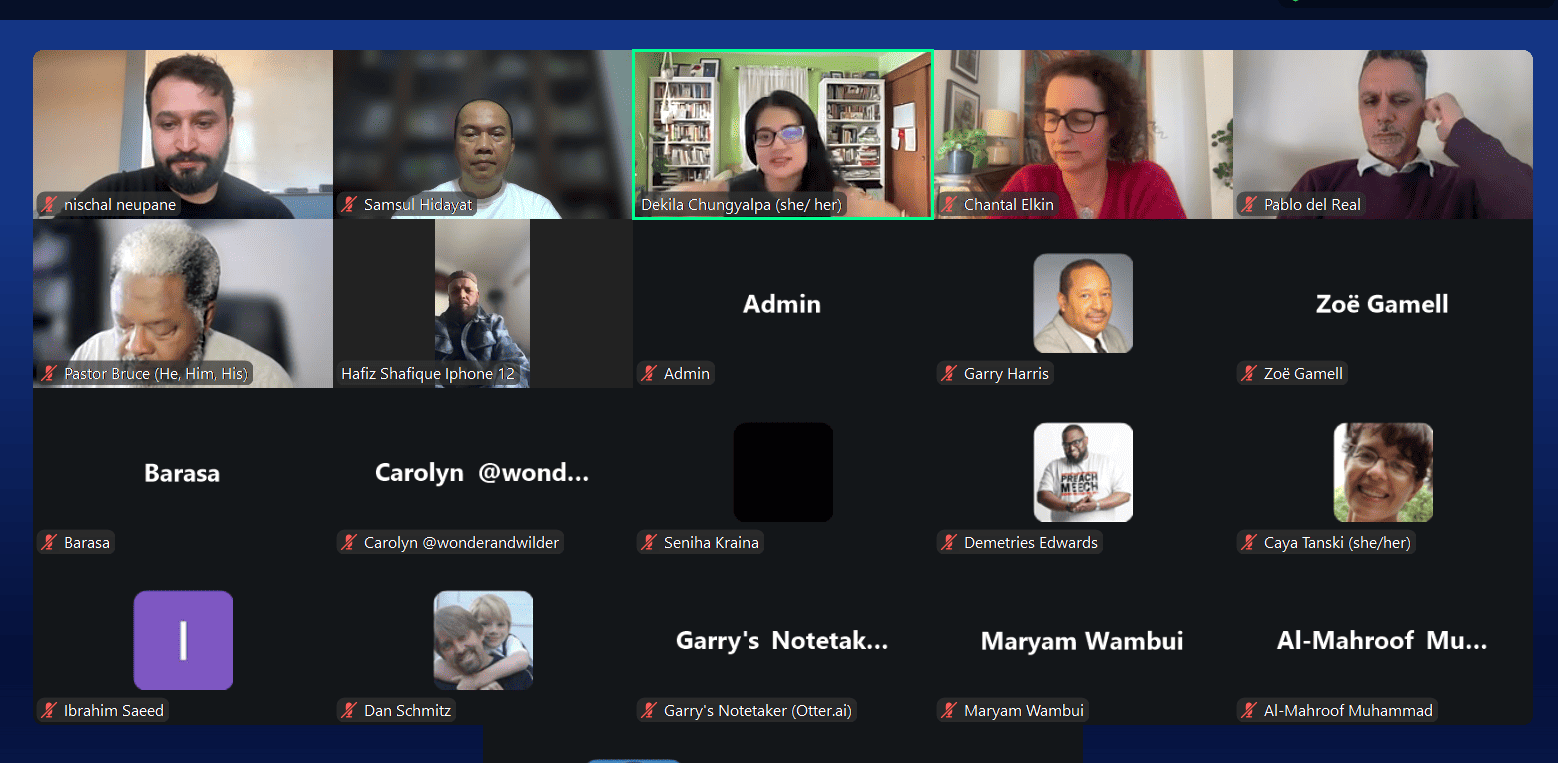
Konservasi Berbasis Iman: Belajar dari Pendekatan Akar Rumput Global
Madison, Amerika Serikat (09/02/2026) Dalam salah satu sesi penting program Preparing Religious Environmental Plans (PREP), peserta diajak untuk meninjau ulang cara kerja konservasi lingkungan yang kerap terlalu teknokratis dan jauh dari realitas komunitas. Sesi ini menghadirkan Chantal Elkin, sosok yang selama puluhan tahun berada di garis depan upaya konservasi internasional dan kini memimpin pendekatan yang lebih dialogis antara iman, nilai, dan lingkungan hidup.
Chantal Elkin saat ini menjabat sebagai Head of Beliefs and Values Program di World Wildlife Fund (WWF). Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam konservasi internasional, ia dikenal luas atas kiprahnya dalam perlindungan hutan dan satwa liar, khususnya dalam isu perdagangan satwa liar ilegal yang menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati global. Namun yang membedakan Elkin dari banyak pakar konservasi lainnya adalah fokus panjangnya pada relasi antara agama, nilai-nilai keimanan, dan praktik konservasi.
Dalam pemaparannya, Elkin menegaskan bahwa krisis lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan ilmiah atau kebijakan dari atas ke bawah. Menurutnya, di banyak wilayah dunia—terutama di Global South—nilai-nilai agama justru menjadi bahasa moral yang paling dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. “Jika kita ingin perubahan yang bertahan lama, kita harus berbicara dengan nilai yang hidup dalam komunitas,” tegasnya.
Elkin berbagi pengalamannya bekerja dengan komunitas agama di berbagai negara, mulai dari Afrika, Asia, hingga Amerika Latin. Ia menunjukkan bahwa ketika pemimpin iman dilibatkan sejak awal sebagai mitra sejajar—bukan sekadar target sosialisasi—maka program konservasi memiliki peluang lebih besar untuk diterima, dijaga, dan diwariskan lintas generasi. Pendekatan ini, menurutnya, jauh lebih efektif dibandingkan proyek konservasi yang hanya berfokus pada indikator teknis tanpa memperhatikan konteks sosial dan spiritual.
Salah satu pesan kunci yang ditekankan Elkin adalah pentingnya menghindari konservasi simbolik. Ia mengingatkan bahwa banyak inisiatif gagal karena hanya menjadikan partisipasi komunitas sebagai formalitas, sementara keputusan inti tetap berada di tangan aktor eksternal. Bagi Elkin, konservasi sejati harus memberi ruang bagi komunitas—termasuk komunitas iman—untuk ikut menentukan arah, prioritas, dan cara kerja proyek sejak awal hingga akhir.
Dalam sesi diskusi, isu keterbatasan sumber daya juga menjadi perhatian utama. Elkin menanggapi kekhawatiran peserta dari komunitas kecil dengan menegaskan bahwa konservasi tidak selalu membutuhkan dana besar. “Yang paling penting adalah relasi, kepercayaan, dan konsistensi,” ujarnya. Ia mencontohkan praktik sederhana seperti perubahan perilaku konsumsi, perlindungan wilayah sakral, hingga pendidikan lingkungan berbasis rumah ibadah sebagai langkah awal yang realistis dan berdampak.
Bagi Samsul Hidayat, sebagai peserta PREP dari Indonesia, pemikiran Elkin terasa sangat relevan. Di banyak daerah, termasuk Kalimantan Barat, isu deforestasi, kebakaran hutan, dan degradasi satwa liar tidak dapat dilepaskan dari nilai, keyakinan, dan cara pandang masyarakat terhadap alam. Pendekatan yang ditawarkan Elkin membuka ruang bagi kerja sama yang lebih setara antara lembaga konservasi global dan komunitas lokal berbasis iman.
Sesi ini menegaskan bahwa iman bukanlah hambatan bagi konservasi, melainkan potensi besar yang selama ini sering diabaikan. Dengan pengalaman panjangnya di WWF dan jejaring global konservasi, Chantal Elkin menunjukkan bahwa masa depan perlindungan lingkungan akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjembatani sains, nilai, dan keyakinan dalam satu gerak bersama. Sesi ini juga membuka ruang refleksi bagi para peserta lintas negara. Samsul Hidayat, peserta PREP dari Indonesia, mengangkat pertanyaan yang merepresentasikan kegelisahan banyak komunitas iman di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah Global South. Ia menyoroti keterbatasan sumber daya yang kerap menjadi penghalang awal keterlibatan komunitas agama dalam isu lingkungan.

Dalam refleksinya, Samsul mempertanyakan bagaimana komunitas iman kecil di tingkat lokal dapat memulai kerja konservasi dengan sumber daya yang sangat terbatas, sekaligus menanyakan kesalahan-kesalahan umum apa yang sebaiknya dihindari oleh kelompok berbasis iman ketika mulai membangun kemitraan lingkungan. Pertanyaan ini muncul dari pengalaman lapangan di mana semangat komunitas sering kali tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas teknis, akses pendanaan, maupun jejaring yang memadai.
Menanggapi kegelisahan tersebut, pemaparan Elkin sebelumnya memberikan kerangka jawab yang relevan. Ia menegaskan bahwa konservasi berbasis iman tidak harus dimulai dari proyek besar, melainkan dari praktik kecil yang konsisten dan bermakna secara spiritual. Dalam pandangan ini, kesalahan yang paling sering terjadi justru ketika komunitas mencoba meniru model proyek besar tanpa mempertimbangkan konteks lokal, atau ketika kemitraan dibangun secara tergesa-gesa tanpa kesetaraan peran dan kejelasan nilai bersama.
Bagi Samsul, dialog ini memperkuat keyakinan bahwa kerja lingkungan berbasis iman harus berangkat dari kejujuran atas keterbatasan, sekaligus keberanian untuk memulai dari apa yang dimiliki: relasi sosial, kepercayaan komunitas, dan otoritas moral pemimpin agama. Dalam konteks Indonesia—di mana rumah ibadah, pesantren, dan organisasi keagamaan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat—pendekatan ini membuka peluang besar bagi konservasi yang lebih berakar, inklusif, dan berkelanjutan.
Tambahan refleksi ini mempertegas pesan utama sesi PREP bersama Chantal Elkin: bahwa masa depan konservasi tidak hanya ditentukan oleh skala pendanaan atau kecanggihan metode, tetapi oleh kemampuan membangun kemitraan yang rendah hati, kontekstual, dan setia pada nilai-nilai yang hidup di tengah komunitas.


